Inilah Mengapa DPR Tetap Bertahan Meski Disorot Publik

VOXBLICK.COM - Seringkali saat ada kebijakan yang tidak populer atau kinerja dewan yang dianggap mengecewakan, seruan untuk bubarkan DPR menggema di media sosial. Rasanya emosi publik memuncak dan jalan pintas itu terlihat paling memuaskan. Tapi, faktanya, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Presiden tidak punya wewenang untuk membubarkan parlemen. Ide pembubaran DPR lebih cocok untuk sistem parlementer, di mana eksekutif dan legislatif bisa saling menjatuhkan. Konstitusi kita, UUD 1945, dirancang dengan prinsip checks and balances, di mana kedua lembaga ini sejajar dan saling mengawasi. Jadi, jika pembubaran DPR bukan pilihan, apakah artinya kita pasrah saja? Tentu tidak. Konstitusi justru sudah menyiapkan sejumlah jalur resmi untuk memastikan akuntabilitas anggota DPR tetap terjaga. Ini bukan jalan pintas, melainkan proses yang terstruktur dan legal. Memahami mekanisme konstitusional DPR ini penting agar energi publik tidak habis untuk menyuarakan hal yang mustahil, melainkan fokus pada cara-cara yang benar-benar bisa membawa perubahan. Jalan untuk menuntut anggota DPR memang ada, dan semuanya sudah tertuang dalam aturan main negara.
Mengapa DPR Tidak Bisa Dibubarkan Begitu Saja?
Untuk memahami mengapa wacana pembubaran DPR tidak relevan di Indonesia, kita perlu melihat dasar sistem pemerintahan kita. Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial.
Ciri utamanya adalah Presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di sisi lain, ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang anggotanya juga dipilih langsung dalam pemilu. Dalam kerangka ini, posisi Presiden dan DPR adalah setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti sering menekankan bahwa desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances). Presiden tidak bisa seenaknya membubarkan DPR, dan sebaliknya, DPR juga tidak bisa sembarangan menjatuhkan Presiden tanpa melalui prosedur pemakzulan yang sangat ketat. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam UUD 1945. Pasal 7C UUD 1945 menyatakan, "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat." Titik. Pasal ini menjadi benteng konstitusional yang membuat wacana pembubaran DPR tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Berbeda dengan negara bersistem parlementer seperti Inggris atau Australia, di mana perdana menteri (kepala pemerintahan) bisa meminta kepala negara untuk membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu sela jika kehilangan kepercayaan mayoritas. Di Indonesia, masa jabatan anggota DPR sudah pasti lima tahun, sama seperti Presiden. Jadi, alih-alih berandai-andai soal pembubaran DPR, lebih strategis untuk memahami dan memanfaatkan alat yang ada untuk menuntut akuntabilitas anggota DPR selama mereka menjabat.
Jalan Lain Menuju Akuntabilitas: Tiga Mekanisme Konstitusional DPR
Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) telah menyediakan setidaknya tiga jalur utama untuk memastikan
fungsi pengawasan berjalan dan akuntabilitas anggota DPR dapat dituntut. Ini adalah alat sesungguhnya untuk mengontrol kekuasaan legislatif.
Pengawasan Lewat Hak-hak DPR: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat
Ini adalah perangkat pengawasan paling fundamental yang dimiliki DPR terhadap pemerintah. Meskipun ditujukan untuk mengawasi eksekutif, penggunaan hak-hak ini oleh anggota dewan menjadi tolak ukur kinerja dan akuntabilitas mereka kepada publik.
Ketika DPR diam seribu bahasa atas kebijakan pemerintah yang meresahkan, publik bisa menuntut anggota DPR untuk menggunakan hak-hak ini. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bayangkan ini seperti seorang manajer yang memanggil stafnya untuk menjelaskan sebuah proyek besar. DPR, atas nama rakyat, bertanya "kenapa kebijakan ini dibuat? apa dasarnya? bagaimana dampaknya?". Ini adalah mekanisme konstitusional DPR yang paling awal untuk membuka tabir sebuah kebijakan. Prosesnya jelas: diusulkan minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi, lalu dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui. Jika jawaban pemerintah dalam interpelasi tidak memuaskan, DPR bisa menaikkan levelnya ke Hak Angket. Ini adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket jauh lebih kuat dari interpelasi. DPR bisa membentuk panitia khusus (pansus) yang punya wewenang memanggil paksa pejabat negara, warga negara, hingga meminta dokumen rahasia. Contoh paling terkenal adalah Pansus Angket Bank Century. Penggunaan hak angket adalah salah satu cara paling ampuh untuk menuntut akuntabilitas pemerintah, dan publik berhak menagih para wakilnya untuk berani menggunakan senjata ini saat diperlukan. Setelah interpelasi atau angket selesai, DPR bisa menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Ini adalah hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Pendapat ini bisa berujung pada rekomendasi kebijakan hingga menjadi pintu masuk untuk proses pemakzulan. Ketiga hak ini adalah satu rangkaian proses pengawasan yang menunjukkan bagaimana mekanisme konstitusional DPR bekerja secara sistematis.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD): Penjaga Etik Internal
Jika hak-hak di atas ditujukan untuk mengawasi pemerintah, maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah mekanisme untuk mengawasi perilaku para anggota dewan itu sendiri. MKD adalah alat kelengkapan dewan yang bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Inilah jalur utama untuk menuntut anggota DPR secara individu atas dugaan pelanggaran kode etik. Publik bisa mengadukan anggota dewan ke MKD. Menurut informasi yang bisa diakses di situs resmi DPR RI, laporan bisa datang dari pimpinan DPR, anggota DPR lain, atau masyarakat. Pelanggaran yang ditangani beragam, mulai dari masalah etika sederhana seperti ketidakhadiran dalam rapat, pernyataan yang tidak pantas, hingga dugaan pelanggaran hukum berat seperti korupsi atau konflik kepentingan. Sanksi yang bisa dijatuhkan MKD pun bertingkat, dari yang paling ringan seperti teguran lisan, sanksi administratif, pemberhentian dari jabatan di alat kelengkapan dewan, hingga yang terberat yaitu pemberhentian sebagai anggota DPR. Proses ini melibatkan verifikasi, penyelidikan, dan persidangan etik yang (seharusnya) terbuka. Namun, MKD seringkali mendapat sorotan tajam. Publik kerap memandangnya sebagai lembaga yang masuk angin karena anggotanya adalah sesama politisi, sehingga ada potensi konflik kepentingan dan solidaritas korps yang menghambat penegakan aturan. Meskipun begitu, MKD tetap merupakan satu-satunya jalur formal internal untuk menuntut akuntabilitas anggota DPR dari sisi etik. Alih-alih mencemooh, tekanan publik yang konsisten justru bisa memaksa MKD untuk bekerja lebih serius dan transparan.
Partisipasi Publik dan Pengawasan Eksternal
Selain mekanisme internal di atas, akuntabilitas anggota DPR juga sangat bergantung pada pengawasan dari luar tembok Senayan. Inilah ranah di mana publik memegang peranan kunci. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif warganya, tidak hanya saat pemilu. Pengawasan oleh media dan masyarakat sipil (CSO/NGO) adalah pilar penting. Organisasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) atau Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK) secara rutin memantau kinerja legislasi, anggaran, dan perilaku anggota dewan. Laporan dan analisis mereka menjadi amunisi bagi publik untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Informasi yang disajikan di sini bersifat edukatif dan bukan merupakan nasihat hukum profesional, namun merujuk pada analisis dari berbagai lembaga kredibel sangat dianjurkan. Seperti yang dijelaskan dalam berbagai publikasi, contohnya di Hukumonline, data mengenai kehadiran rapat, rekam jejak legislasi, hingga laporan harta kekayaan adalah informasi publik yang bisa diakses dan dikritisi. Demonstrasi dan kampanye di media sosial juga merupakan bentuk tekanan politik yang sah. Ketika sebuah RUU kontroversial dibahas, tekanan publik yang masif terbukti beberapa kali mampu menunda atau bahkan membatalkan pengesahannya. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat, jika disalurkan secara masif dan terorganisir, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan di DPR. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari mekanisme menuntut anggota DPR untuk mendengarkan aspirasi konstituennya. Pada akhirnya, meski pembubaran DPR adalah fantasi politik yang tidak konstitusional, jalur untuk meminta pertanggungjawaban sangatlah nyata dan beragam. Mulai dari penggunaan hak interpelasi dan hak angket untuk mengorek kebijakan pemerintah, melaporkan pelanggaran etik ke Mahkamah Kehormatan Dewan, hingga pengawasan ketat dari publik, media, dan masyarakat sipil. Semua ini adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang dirancang untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Memahami dan memanfaatkan mekanisme konstitusional DPR ini secara efektif adalah tugas kita bersama sebagai warga negara. Daripada berteriak bubarkan, mungkin lebih produktif untuk bertanya, sudahkah semua alat pengawasan ini kita gunakan secara maksimal?. Sebab, akuntabilitas anggota DPR tidak datang dari ruang hampa, melainkan dari pengawasan yang tak pernah lelah.
Apa Reaksi Anda?
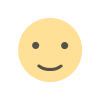 Suka
0
Suka
0
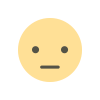 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
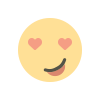 Cinta
0
Cinta
0
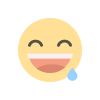 Lucu
0
Lucu
0
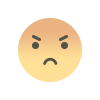 Marah
0
Marah
0
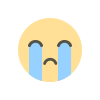 Sedih
0
Sedih
0
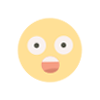 Wow
0
Wow
0
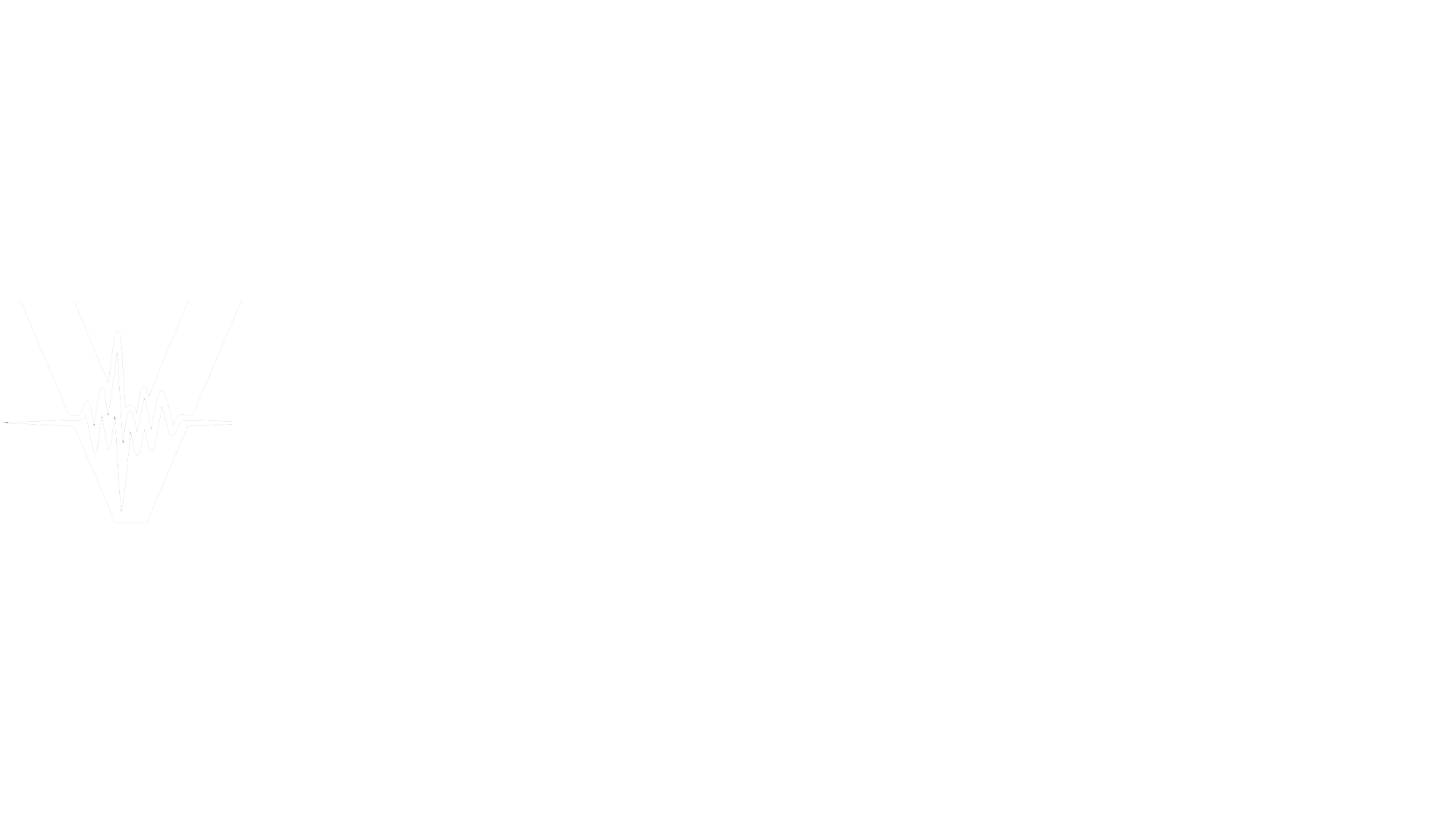











































![[VIDEO ]Sejarah Internet, Dari ARPANET Menuju Jaringan Global Era Digital](https://img.youtube.com/vi/MDcU6GohRxM/maxresdefault.jpg)
![[VIDEO] Bagaimana Internet Mengubah Cara Kita Mengonsumsi Berita](https://img.youtube.com/vi/h2dxyFmTk28/maxresdefault.jpg)
![[VIDEO] Inovasi Teknologi Penyiaran: Membangun Identitas dan Kebangsaan](https://img.youtube.com/vi/ies8UB0Cmeg/maxresdefault.jpg)





















