Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Bisakah Presiden Bubarkan DPR Lagi?

Kondisi Genting yang Melahirkan Dekrit Kontroversial
VOXBLICK.COM - Tanggal 5 Juli 1959 menjadi salah satu hari paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Saat itu, Presiden Soekarno, dengan dukungan penuh dari Angkatan Darat, mengeluarkan sebuah keputusan yang mengubah total peta politik negara: Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya tegas dan radikal, yaitu membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan mengakhiri era Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Langkah ini secara efektif menjadi awal dari periode yang kita kenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Namun, keputusan dramatis ini tidak datang dari ruang hampa. Untuk memahaminya, kita perlu mundur sejenak ke suasana politik akhir tahun 1950-an. Sejak Pemilu 1955, Indonesia memiliki sebuah badan bernama Konstituante, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Tugasnya mulia sekaligus berat: merumuskan konstitusi baru yang permanen untuk menggantikan UUDS 1950. Sayangnya, harapan besar itu kandas di tengah jalan. Selama hampir empat tahun bersidang, para anggota Konstituante terjebak dalam perdebatan ideologis yang tak berkesudahan, terutama soal dasar negara. Tarik-menarik antara kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara dan kelompok yang memperjuangkan Islam (melalui Piagam Jakarta) menciptakan kebuntuan total. Voting berkali-kali dilakukan, tetapi tidak pernah mencapai kuorum dua pertiga yang disyaratkan. Suasana politik pun memanas, kabinet jatuh bangun, dan pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta menambah runyam situasi. Negara seolah berada di ambang perpecahan. Dalam situasi inilah Soekarno melihat adanya sebuah krisis yang mengancam persatuan bangsa, yang menurutnya memerlukan tindakan darurat. Kegagalan Konstituante menjadi justifikasi utama bagi lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Isi dan Kekuatan Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit yang dibacakan di Istana Merdeka itu memiliki tiga poin utama yang sangat fundamental. Pertama, pembubaran Konstituante, lembaga yang dipilih rakyat namun dianggap gagal total dalam menjalankan tugasnya. Kedua, penetapan bahwa UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Langkah ini adalah sebuah intervensi eksekutif yang luar biasa kuat terhadap proses legislatif dan konstitusional. Secara hukum, langkah ini sangat kontroversial. Jika merujuk pada UUDS 1950 yang berlaku saat itu, presiden tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembubaran lembaga legislatif atau mengubah konstitusi secara sepihak. Soekarno dan para pendukungnya, terutama dari kalangan militer yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution, mendasarkan tindakan ini pada konsep hukum darurat negara atau staatsnoodrecht. Argumennya adalah negara dalam keadaan bahaya yang memaksa presiden sebagai kepala negara untuk mengambil tindakan di luar hukum (ekstra-konstitusional) demi menyelamatkan bangsa. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memang merupakan sebuah tindakan revolusioner yang melampaui kerangka konstitusi yang ada. Namun, kekuatan hukumnya kemudian dilegitimasi oleh berbagai produk hukum turunannya dan pengakuan dari lembaga-lembaga negara, termasuk MPRS yang dibentuk setelahnya. Langkah ini secara efektif menciptakan sebuah tatanan hukum baru yang berpusat pada UUD 1945 versi asli, yang memberikan porsi kekuasaan lebih besar kepada presiden.
Dampak Langsung: Panggung untuk Demokrasi Terpimpin
Dampak dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terasa seketika. Sistem demokrasi parlementer yang liberal dan multipartai langsung berakhir.
Indonesia memasuki babak baru yang disebut Demokrasi Terpimpin, di mana Soekarno menjadi figur sentral dengan kekuasaan yang sangat dominan. Dengan kembalinya UUD 1945 (versi sebelum amandemen), posisi presiden menjadi sangat kuat, tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ini adalah perubahan drastis dari sistem sebelumnya di mana perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Sejarah Indonesia mencatat periode ini sebagai era di mana kekuasaan terpusat di tangan satu orang. Lembaga legislatif pun mengalami pelemahan signifikan. Meskipun DPR hasil Pemilu 1955 tidak langsung dibubarkan oleh dekrit tersebut, nasibnya berakhir setahun kemudian. Pada tahun 1960, ketika DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, Soekarno tanpa ragu melakukan pembubaran lembaga legislatif tersebut dan menggantinya dengan DPR-Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya ia tunjuk sendiri. Ini adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan eksekutif menjadi superior atas legislatif. Partai-partai politik yang dianggap berseberangan dengan haluan pemerintah, seperti Masyumi dan PSI, dibubarkan. Konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) yang digagas Soekarno menjadi pilar utama politik, yang mencoba menyatukan tiga kekuatan besar saat itu. Pada akhirnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bukan hanya soal konstitusi, tetapi juga soal pergeseran fundamental keseimbangan kekuasaan yang membentuk arah sejarah Indonesia untuk dekade berikutnya.
Mungkinkah Sejarah Pembubaran Lembaga Legislatif Terulang?
Pertanyaan ini sering muncul, terutama saat tensi politik antara eksekutif dan legislatif memanas.
Apakah presiden di era reformasi ini bisa melakukan langkah serupa dengan yang dilakukan Soekarno? Jawabannya, jika kita melihat kerangka hukum saat ini, adalah: hampir tidak mungkin. Ada perbedaan fundamental antara kondisi hukum dan politik tahun 1959 dengan sekarang. Setelah tumbangnya Orde Baru, bangsa Indonesia melakukan amandemen besar-besaran terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002). Amandemen ini dirancang khusus untuk mencegah terulangnya pemusatan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi di masa lalu. Berikut beberapa benteng konstitusional yang ada saat ini:
1. Mekanisme Pemberhentian Presiden yang Jelas
UUD 1945 hasil amandemen kini memuat pasal-pasal yang sangat rinci mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden (impeachment), yaitu Pasal 7A dan 7B.
Prosesnya sangat panjang dan melibatkan tiga lembaga negara: DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. DPR berfungsi sebagai penyelidik awal, MK yang memutuskan apakah presiden terbukti melanggar hukum, dan MPR yang memegang palu putusan akhir. Dengan mekanisme ini, presiden tidak bisa diberhentikan hanya karena alasan politik, dan sebaliknya, presiden juga tidak bisa seenaknya membubarkan DPR.
2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK)
Ini adalah salah satu inovasi terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution).
Salah satu kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Jika hari ini ada presiden yang mencoba mengeluarkan dekrit untuk pembubaran lembaga legislatif, tindakan tersebut akan dengan mudah digugat dan kemungkinan besar dibatalkan oleh MK karena jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945.
3. Keseimbangan Kekuasaan Antar Lembaga Negara
Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Kini, tidak ada lagi lembaga tertinggi. Semua lembaga tinggi negara (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK) memiliki kedudukan yang setara dengan kewenangan masing-masing yang diatur dalam konstitusi. Prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) menjadi pilar utama. Presiden tidak bisa lagi mendikte lembaga lain, termasuk DPR. Sebaliknya, DPR juga punya kekuatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut analisis dari para pakar hukum tata negara, seperti Bivitri Susanti dari PSHK, penggunaan dalih kegentingan memaksa untuk melangkahi konstitusi kini jauh lebih sulit dilakukan karena setiap tindakan pemerintah bisa diuji secara hukum. Perlu diingat, interpretasi terhadap peristiwa sejarah dan potensi masa depan dalam politik selalu dinamis. Analisis ini didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku saat ini, yang tentu saja bisa berubah seiring waktu dan dinamika politik. Meski secara hukum tindakan pembubaran lembaga legislatif seperti pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sulit terulang, pelajaran dari sejarah tetaplah relevan. Semangat untuk menabrak aturan main demi kekuasaan atau stabilitas semu adalah godaan yang selalu ada dalam politik. Peristiwa bersejarah seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengingatkan kita bahwa konstitusi dan lembaga demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi. Ia harus terus dijaga dan dirawat oleh seluruh elemen bangsa. Kewaspadaan publik dan komitmen para elite politik terhadap supremasi hukum menjadi kunci agar sejarah kelam pemusatan kekuasaan tidak kembali menghantui perjalanan demokrasi Indonesia.
Apa Reaksi Anda?
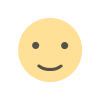 Suka
0
Suka
0
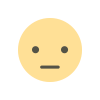 Tidak Suka
0
Tidak Suka
0
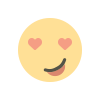 Cinta
0
Cinta
0
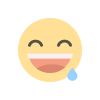 Lucu
0
Lucu
0
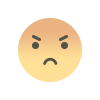 Marah
0
Marah
0
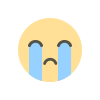 Sedih
0
Sedih
0
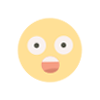 Wow
0
Wow
0
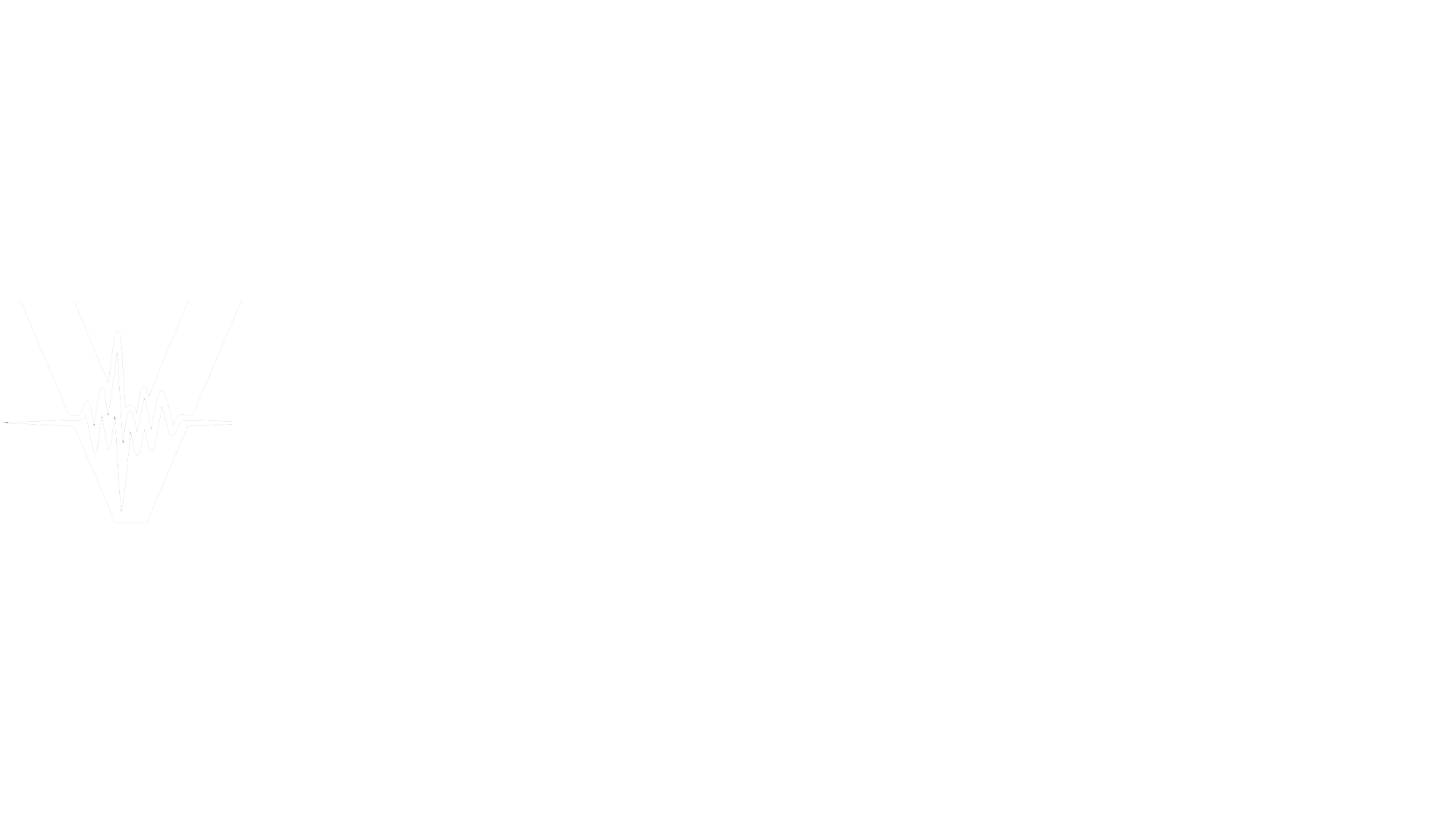











































![[VIDEO ]Sejarah Internet, Dari ARPANET Menuju Jaringan Global Era Digital](https://img.youtube.com/vi/MDcU6GohRxM/maxresdefault.jpg)
![[VIDEO] Bagaimana Internet Mengubah Cara Kita Mengonsumsi Berita](https://img.youtube.com/vi/h2dxyFmTk28/maxresdefault.jpg)
![[VIDEO] Inovasi Teknologi Penyiaran: Membangun Identitas dan Kebangsaan](https://img.youtube.com/vi/ies8UB0Cmeg/maxresdefault.jpg)




















